Headline
BUMN Siaga Guncangan
Pemerintah mengimbau penempatan yang lebih lama atas devisa hasil ekspor, misalnya berbentuk deposito. Penempatan itu bakal dibebaskan dari pajak.
Pemerintah mengimbau penempatan yang lebih lama atas devisa hasil ekspor, misalnya berbentuk deposito. Penempatan itu bakal dibebaskan dari pajak.
Kurangnya sosialisasi dan harmonisasi kebijakan antara Kemendikbud-Ristek dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan menjadi pencetus permasalahan dalam proses PPDB.


Apple telah menghapus aplikasi WhatsApp milik Meta dan Threads dari App Store-nya di Tiongkok setelah mendapatkan perintah dari regulator internet teratas negara itu.



Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah perempuan yang memulai bisnis selama pandemi, dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kaum pria.


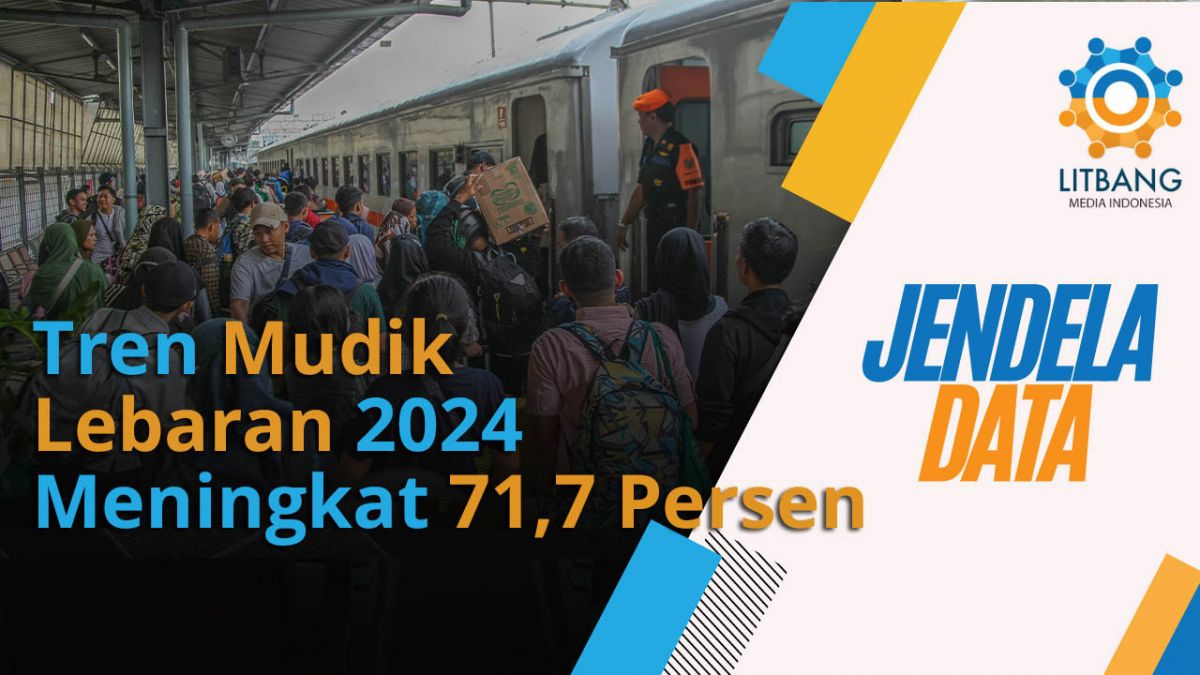
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2024 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved








