Headline
Bola Deeskalasi di Sekutu Israel
Konflik regional antara Israel dan Iran memunculkan potensi perselisihan lebih besar yang bahkan bisa mengarah pada Perang Dunia III.
Konflik regional antara Israel dan Iran memunculkan potensi perselisihan lebih besar yang bahkan bisa mengarah pada Perang Dunia III.
Kurangnya sosialisasi dan harmonisasi kebijakan antara Kemendikbud-Ristek dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan menjadi pencetus permasalahan dalam proses PPDB.


Saat ini konflik di Timur Tengah semakin memanas, tidak hanya antara Palestina dengan Israel. Kini konflik di Timur Tengah bertambah meluas antara Iran dan Israel.
Para pejabat Israel belum memberikan komentar publik mengenai apa yang terjadi pada hari Jumat, dan para analis mengatakan kuntuk saat ini kedua belah pihak berupaya melakukan deeskalasi.


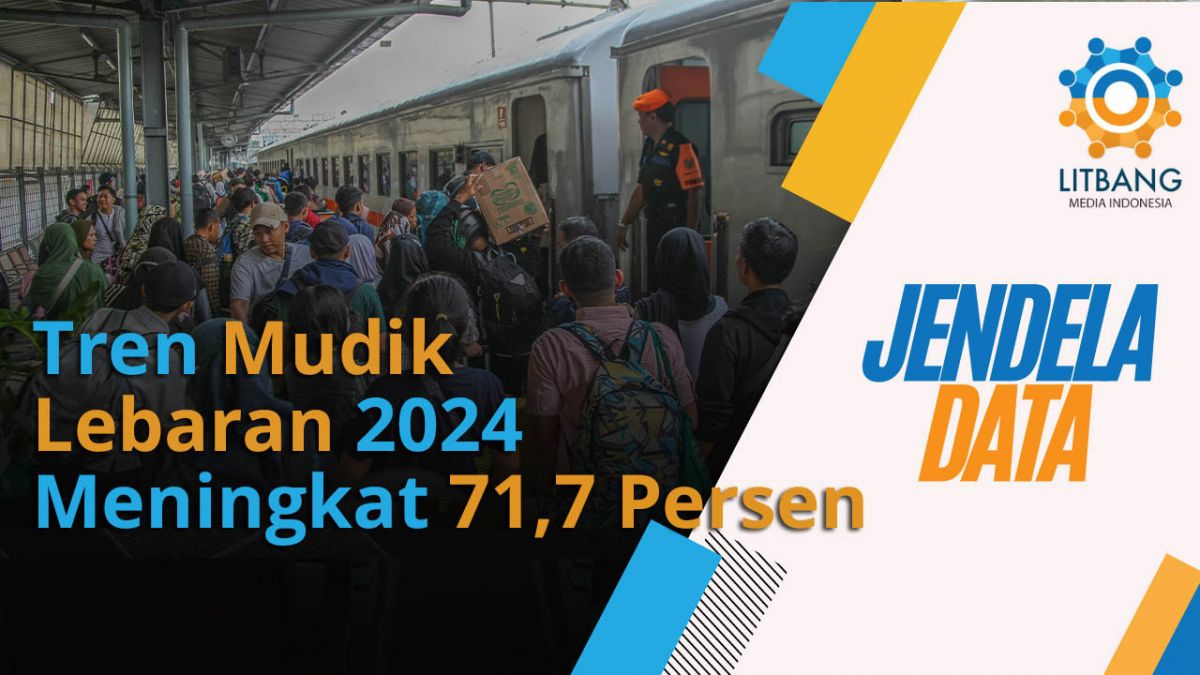
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2024 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved







