Headline
BUMN Siaga Guncangan
Pemerintah mengimbau penempatan yang lebih lama atas devisa hasil ekspor, misalnya berbentuk deposito. Penempatan itu bakal dibebaskan dari pajak.
Pemerintah mengimbau penempatan yang lebih lama atas devisa hasil ekspor, misalnya berbentuk deposito. Penempatan itu bakal dibebaskan dari pajak.
Kurangnya sosialisasi dan harmonisasi kebijakan antara Kemendikbud-Ristek dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan menjadi pencetus permasalahan dalam proses PPDB.


Mereka mengatakan “tidak ada serangan rudal untuk saat ini” di negara itu, setelah ledakan terdengar di dekat pusat kota Isfahan.



Penutupan jalan akibat kebakaran, kawasan Mampang Prapatan mengalami macet parah.

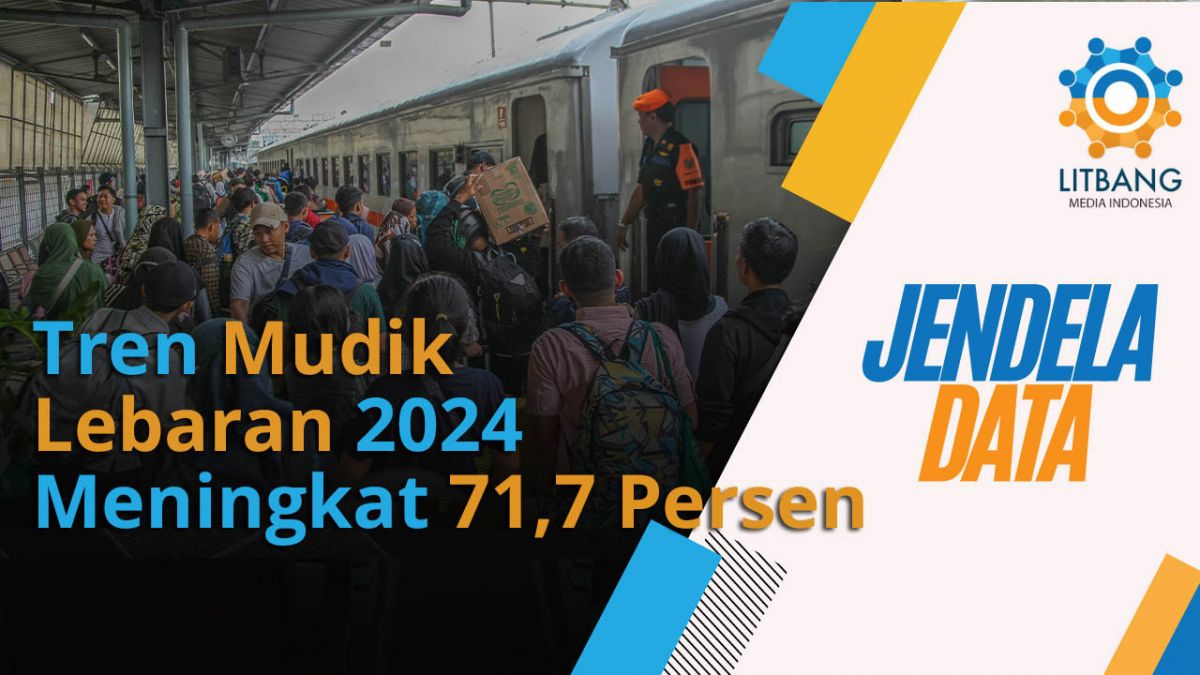

Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2024 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved







